Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 26 Desember 2020 |
TAHUN 2020 sejumlah selebriti yang terjerat kasus prostitusi daring justru lenggang kangkung seolah tak bikin gaduh, tak buat salah. Otoritas penegak hukum tidak mampu menjangkau si selebriti. Tidak ada yang baru sesungguhnya. Semua merupakan pengulangan situasi-situasi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
Otoritas penegak hukum boleh jadi berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Kalau mau benar-benar konsekuen, otoritas penegak hukum seharusnya ’’bekerja lebih maksimal’’ dengan memproses sesuai dengan ketentuan agar kepada para artis itu diberikan ganti rugi (restitusi) selaku korban perdagangan orang.
Di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam UU TPPO, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang. UU TPPO kentara dilandaskan pada Konvensi PBB Tahun 1949 untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi. Esensinya, perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi dan pelacuran dipandang mengandung praktik serupa. Karena keduanya diposisikan sama, secara logis berlakulah dekriminalisasi pelacuran. Indonesia hingga kini masih tergolong negara yang menerapkan pendekatan dekriminalisasi parsial terhadap pelacuran.
Menyerupai Swedish model, germo dan konsumen si pelacur menjadi target sanksi hukum. Sedangkan si pelacur sendiri terproteksi dan dibantu agar keluar dari kondisi tereksploitasi. Penerapan dekriminalisasi pula yang berdasar kajian menyebabkan otoritas penegak hukum tidak menempatkan pelacuran sebagai prioritas kerjanya.
Sejak disahkan pada 2007, UU TPPO kini tertatih-tatih mengejar perkembangan dunia pelacuran yang kian canggih. ’’Penyamarataan antara pelacuran dan perdagangan orang abai terhadap realitas bahwa dewasa ini sebagian yang menjadi pelacur adalah orang yang memilih berdasar perhitungan ekonomis untung-rugi. Si pelacur berkehendak dan memutuskan sendiri, tanpa dipaksa, menjadi penjaja seks. Dia adalah pelaku aktif dalam bisnis lendir.
Variasi pelacuran itulah yang lantas dirumuskan dalam The 1995 Platform of Action pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Yakni, ada involuntary prostitution (forced prostitution) dan ada voluntary prostitution.
Para selebriti merangkap pelacur yang diringkus kepolisian, berdasar perlakuan hukum yang mereka terima, tampaknya disikapi sebagai involuntary prostitute. Padahal, amat mungkin para pelacur kelas kakap tersebut adalah voluntary prostitute.
Pembedaan dua tipe pelacur(an) tersebut sepatutnya berimplikasi pada perlunya mekanisme penanganan yang berbeda satu sama lain, bergantung pada jenis pelacuran yang sedang ditangani. Pelacur yang menggeluti bidang tersebut berdasar keinginannya sendiri, bahkan memperoleh pendapatan dalam jumlah fantastis serta mempekerjakan manajer laiknya pekerja profesional, dapat disetarakan sebagai pekerja seks profesional (PSK).
Berbeda dengan mereka yang dipaksa atau dieksploitasi menjadi pelacur sehingga dapat disebut sebagai budak seks. Pelacur yang termasuk dalam tipe PSK (voluntary prostitute) meruntuhkan dasar berpikir UU TPPO bahwa pelacuran merupakan praktik perdagangan orang. Unsur eksploitasi tidak ada di dalam praktik pelacuran seperti itu.
Pelacur semacam itu secara sengaja dan sukarela tidak memfungsikan keberdayaannya –baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial– untuk mengelak atau keluar dari dunia pelacuran. Mereka bukan korban perdagangan orang, melainkan pelaku perdagangan layanan seksual.
Realitasnya, di sini ada kekacauan berpikir-bekerja. Pelacuran tidak dibenarkan, tetapi penindakan juga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh akibat anggapan bahwa pelacuran adalah perdagangan orang.
Kekacauan itu memantik sinisme di tengah masyarakat. Getahnya mengena ke kepolisian. Pemberian status korban kepada artis yang tertangkap basah sebagai pelacur daring dirasakan publik laksana menerabas pagar moral, bahkan menggagahi akal sehat.
Atas dasar itu, ihwal tipe-tipe pelacuran mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi pasal-pasal –utamanya– UU TPPO dan UU KUHP. Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi.
Merevisi UU butuh waktu tidak sebentar. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, dari pintu yang lain, masing-masing pemerintah daerah dapat menyusun larangan maupun mempertegas ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan tempat-tempat penginapan sebagai lokasi transaksi narkoba, pelacuran, dan bisnis-bisnis terlarang lainnya.
Baca Juga: Covid-19 Penipu Ulung, Ahli Ungkap Ruam Kulit Pada Dewi Perssik
Bersamaan dengan itu, sanksi sosial harus bisa ditegakkan tanpa menunggu revisi UU. Ambil misal, rumah-rumah produksi berhenti mengontrak artis yang kedapatan menjadi pelacur. Kepada artis-artis itu juga tak perlu disandangkan penamaan eufemistis. Alih-alih PSK, sebut saja mereka adalah pelacur. Komisi Penyiaran Indonesia dapat membuat ketentuan untuk memastikan para pelacur daring tidak muncul di acara-acara yang disiarkan di layar kaca.
Audiens, teristimewa anak-anak, tidak sepantasnya mendapat pelajaran ngawur bahwa dengan diamankan polisi, pelacur-artis justru semakin laris. Juga, untuk memastikan para pelacur-artis itu tidak menjadi agen penyakit menular seksual, kepada mereka dikenakan wajib lapor sekaligus wajib periksa secara rutin di rumah sakit umum daerah.
Akhirulkalam, bolehlah ditanya apa sesungguhnya pekerjaan utama mereka, para artis yang di-OTT polisi saat menjajakan tubuh mereka. Mana sebutan yang lebih tepat: pelacur yang menyambi sebagai artis ataukah artis yang menyambi sebagai pelacur?
Allahu a’lam. (*)
*) Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne
Saksikan video menarik berikut ini:
TAHUN 2020 sejumlah selebriti yang terjerat kasus prostitusi daring justru lenggang kangkung seolah tak bikin gaduh, tak buat salah. Otoritas penegak hukum tidak mampu menjangkau si selebriti. Tidak ada yang baru sesungguhnya. Semua merupakan pengulangan situasi-situasi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
Otoritas penegak hukum boleh jadi berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Kalau mau benar-benar konsekuen, otoritas penegak hukum seharusnya ’’bekerja lebih maksimal’’ dengan memproses sesuai dengan ketentuan agar kepada para artis itu diberikan ganti rugi (restitusi) selaku korban perdagangan orang.
Di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam UU TPPO, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang. UU TPPO kentara dilandaskan pada Konvensi PBB Tahun 1949 untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi. Esensinya, perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi dan pelacuran dipandang mengandung praktik serupa. Karena keduanya diposisikan sama, secara logis berlakulah dekriminalisasi pelacuran. Indonesia hingga kini masih tergolong negara yang menerapkan pendekatan dekriminalisasi parsial terhadap pelacuran.
Menyerupai Swedish model, germo dan konsumen si pelacur menjadi target sanksi hukum. Sedangkan si pelacur sendiri terproteksi dan dibantu agar keluar dari kondisi tereksploitasi. Penerapan dekriminalisasi pula yang berdasar kajian menyebabkan otoritas penegak hukum tidak menempatkan pelacuran sebagai prioritas kerjanya.
Sejak disahkan pada 2007, UU TPPO kini tertatih-tatih mengejar perkembangan dunia pelacuran yang kian canggih. ’’Penyamarataan antara pelacuran dan perdagangan orang abai terhadap realitas bahwa dewasa ini sebagian yang menjadi pelacur adalah orang yang memilih berdasar perhitungan ekonomis untung-rugi. Si pelacur berkehendak dan memutuskan sendiri, tanpa dipaksa, menjadi penjaja seks. Dia adalah pelaku aktif dalam bisnis lendir.
Variasi pelacuran itulah yang lantas dirumuskan dalam The 1995 Platform of Action pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Yakni, ada involuntary prostitution (forced prostitution) dan ada voluntary prostitution.
Para selebriti merangkap pelacur yang diringkus kepolisian, berdasar perlakuan hukum yang mereka terima, tampaknya disikapi sebagai involuntary prostitute. Padahal, amat mungkin para pelacur kelas kakap tersebut adalah voluntary prostitute.
Pembedaan dua tipe pelacur(an) tersebut sepatutnya berimplikasi pada perlunya mekanisme penanganan yang berbeda satu sama lain, bergantung pada jenis pelacuran yang sedang ditangani. Pelacur yang menggeluti bidang tersebut berdasar keinginannya sendiri, bahkan memperoleh pendapatan dalam jumlah fantastis serta mempekerjakan manajer laiknya pekerja profesional, dapat disetarakan sebagai pekerja seks profesional (PSK).
Berbeda dengan mereka yang dipaksa atau dieksploitasi menjadi pelacur sehingga dapat disebut sebagai budak seks. Pelacur yang termasuk dalam tipe PSK (voluntary prostitute) meruntuhkan dasar berpikir UU TPPO bahwa pelacuran merupakan praktik perdagangan orang. Unsur eksploitasi tidak ada di dalam praktik pelacuran seperti itu.
Pelacur semacam itu secara sengaja dan sukarela tidak memfungsikan keberdayaannya –baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial– untuk mengelak atau keluar dari dunia pelacuran. Mereka bukan korban perdagangan orang, melainkan pelaku perdagangan layanan seksual.
Realitasnya, di sini ada kekacauan berpikir-bekerja. Pelacuran tidak dibenarkan, tetapi penindakan juga tidak bisa dilakukan secara menyeluruh akibat anggapan bahwa pelacuran adalah perdagangan orang.
Kekacauan itu memantik sinisme di tengah masyarakat. Getahnya mengena ke kepolisian. Pemberian status korban kepada artis yang tertangkap basah sebagai pelacur daring dirasakan publik laksana menerabas pagar moral, bahkan menggagahi akal sehat.
Atas dasar itu, ihwal tipe-tipe pelacuran mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi pasal-pasal –utamanya– UU TPPO dan UU KUHP. Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi.
Merevisi UU butuh waktu tidak sebentar. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, dari pintu yang lain, masing-masing pemerintah daerah dapat menyusun larangan maupun mempertegas ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan tempat-tempat penginapan sebagai lokasi transaksi narkoba, pelacuran, dan bisnis-bisnis terlarang lainnya.
Baca Juga: Covid-19 Penipu Ulung, Ahli Ungkap Ruam Kulit Pada Dewi Perssik
Bersamaan dengan itu, sanksi sosial harus bisa ditegakkan tanpa menunggu revisi UU. Ambil misal, rumah-rumah produksi berhenti mengontrak artis yang kedapatan menjadi pelacur. Kepada artis-artis itu juga tak perlu disandangkan penamaan eufemistis. Alih-alih PSK, sebut saja mereka adalah pelacur. Komisi Penyiaran Indonesia dapat membuat ketentuan untuk memastikan para pelacur daring tidak muncul di acara-acara yang disiarkan di layar kaca.
Audiens, teristimewa anak-anak, tidak sepantasnya mendapat pelajaran ngawur bahwa dengan diamankan polisi, pelacur-artis justru semakin laris. Juga, untuk memastikan para pelacur-artis itu tidak menjadi agen penyakit menular seksual, kepada mereka dikenakan wajib lapor sekaligus wajib periksa secara rutin di rumah sakit umum daerah.
Akhirulkalam, bolehlah ditanya apa sesungguhnya pekerjaan utama mereka, para artis yang di-OTT polisi saat menjajakan tubuh mereka. Mana sebutan yang lebih tepat: pelacur yang menyambi sebagai artis ataukah artis yang menyambi sebagai pelacur?
Allahu a’lam. (*)
*) Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik The University of Melbourne
Saksikan video menarik berikut ini:
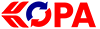
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini