Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 19 April 2025 |

KALBARONLINE.com – Di sebuah negeri antah berantah yang katanya negara hukum, keadilan bukan lagi soal aturan. Tapi soal siapa yang paling piawai merangkai narasi. Dan sekarang, kita baru saja menyaksikan lahirnya satu jurus pamungkas yang mungkin akan disalin oleh banyak pejabat publik ke depan, jurus "bayar utang".
Pola baru ini sederhana tapi mematikan logika. Seorang penyelenggara negara menerima aliran dana miliaran rupiah dari kontraktor proyek pemerintah. Uangnya dipakai untuk berbagai kebutuhan pribadi. Bangun ruko, beli karpet masjid, hingga aktivitas keluarga. Ketika aparat penegak hukum mulai menyorot, jawabannya simpel, "itu bukan gratifikasi, itu orang bayar utang saya."
Tidak ada bukti perjanjian utang, tidak pernah dicatat dalam LHKPN, tidak ada cicilan atau bunga yang lazim dalam transaksi pinjam-meminjam. Tapi cukup dengan satu kalimat sakti itu, semua seolah beres. Dana yang mencurigakan berubah status, bukan gratifikasi, bukan suap, melainkan pelunasan. Suci kembali.
Dan parahnya, jurus ini justru dilontarkan oleh pejabat yang selama ini dikenal religius, santun, dan penuh ayat di podium. Ironisnya, bahkan saat aparat menyita aset yang diduga hasil aliran dana itu, tak ada sedikit pun rasa gentar. Jawabannya lagi-lagi, "itu dibayar orang karena dia berutang pada saya."
Bayangkan jika dalih ini dibakukan. Bayangkan betapa berbahayanya preseden ini bagi hukum dan logika negara. Karena kalau dibiarkan, ini akan jadi template.
“Anda dapat transfer mencurigakan? Bilang saja itu pembayaran utang lama.”
“Anda dapat mobil, rumah, ruko? Itu bukan gratifikasi, itu tukar guling dari transaksi lisan.”
“Anda pejabat dan penerima dana proyek? Tenang, asal narasi utang rapi, semua bisa disulap.”
Tak hanya itu. Logika "bayar utang" juga membuka jalan baru bagi praktik pencucian uang model lokal. Tak perlu akun bank lepas pantai, tak perlu skema rumit ala Panama Papers. Cukup punya kedekatan dengan penguasa proyek, lakukan transaksi lisan, dan ketika ditanya, tinggal jawab, "sudah dibayar."
Pejabat publik bisa menyimpan aset, membangun properti, menikmati fasilitas, dan tetap tampak bersih secara administratif. Karena satu-satunya dokumen yang dibutuhkan adalah narasi.
Ini jelas melawan semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur di negeri antah berantah itu. Karena dalam UU itu, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat negara yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan dalam konteks gratifikasi, beban pembuktian dibalikkan kepada si penerima. Tapi jurus "utang pribadi" tampaknya lebih kuat daripada pasal hukum.
Belum lagi jika dilihat dari aspek moral. Bagaimana mungkin seorang pejabat, yang dipercaya mengelola uang rakyat, bisa bertransaksi miliaran rupiah secara personal dengan kontraktor negara? Kalau memang itu utang pribadi, mengapa tidak pernah dilaporkan sejak awal? Kenapa baru muncul ketika aparat mulai menyelidiki?
Sistem ini sedang dibentuk. Sebuah sistem pembenaran kolektif, di mana siapa pun bisa menyelamatkan diri asal pandai menyusun cerita. Bahkan institusi penegak hukum pun seakan gamang, karena tidak ingin dicap mempolitisasi. Maka muncul-lah kompromi, asal tak terbukti hitam-putih, biarkan abu-abu tetap abu-abu.
Dan publik? Dipaksa percaya. Dipaksa menelan narasi "utang pribadi" seperti kita menelan kenaikan pajak atau harga sembako, dengan diam dan rasa muak.
Coba bayangkan jika logika ini diterapkan di semua sektor. Misalnya, seorang pejabat dinas perizinan menerima hadiah rumah dari pengusaha tambang. Saat ditanya, dia bilang, "Itu pembayaran utang lama waktu saya bantu dia waktu kuliah." Atau bayangkan kepala dinas pendidikan menerima kendaraan mewah dari rekanan penyedia proyek, dan jawabannya adalah, "Dia memang punya utang ke saya waktu saya bantu biaya sekolah anaknya."
Bayangkan pula jika anggota dewan menerima aliran dana dari konsorsium proyek jalan, dan cukup menjawab, "Itu bentuk terima kasih karena dulu saya pernah bantu orangtuanya." Lalu selesai. Tak perlu bukti. Tak perlu pelaporan.
Narasi utang akan jadi benteng baru. Tidak kelihatan di awal, tapi siap muncul saat penyidikan datang. Ia bisa menjadi alasan, sekaligus pelindung. Karena hukum di negeri yang konon katanya menjunjung tinggi keadilan tapi hobi main narasi ini terlalu sering kalah oleh cerita.
Ini berbahaya bukan hanya bagi hukum, tapi bagi generasi berikutnya. Karena yang ditanam adalah contoh buruk, bahwa akal-akalan lebih berguna daripada kejujuran. Bahwa yang penting bukan amanah, tapi pintar bersilat lidah. Bahwa jabatan bukan tanggung jawab, tapi panggung untuk memainkan cerita.
Sementara itu, masyarakat biasa? Hutang Rp5 juta ke bank macet satu minggu saja bisa didatangi debt collector. Tapi ketika pejabat bicara soal utang Rp5 miliar, semua orang harus percaya, dan kalau tidak percaya, dianggap memfitnah.
Di sinilah kita perlu mengembalikan akal sehat publik. Bahwa pinjaman, jika benar, harus tercatat. Harus dilaporkan. Harus diikat perjanjian. Bukan hanya ada ketika dibutuhkan untuk menyelamatkan muka.
Dan aparat penegak hukum pun seharusnya tidak tunduk pada narasi. Seharusnya mampu menembus cerita, menuntut bukti. Karena kalau hanya bergantung pada pengakuan sepihak, maka semua pelaku kejahatan tinggal menghafal satu kalimat ajaib, "Itu karena dia punya utang."
Ini bukan hanya soal satu oknum atau satu kejadian. Ini soal bagaimana kita, sebagai bangsa, mau memelihara sistem keadilan. Apakah kita ingin hukum ditegakkan berdasar logika dan aturan, atau dibengkokkan berdasar cerita?
Publik sebenarnya tak butuh aparat yang galak di depan mikrofon. Publik butuh kepastian bahwa hukum tak bisa dikibuli dengan permainan kata.
Jika negara yang konon katanya masih punya keberanian, yang bahkan kepala negaranya akan mengejar pelaku korupsi sampai ke Antartika, maka setiap narasi "utang pribadi" yang dilempar ke publik harus diuji secara terbuka—di pengadilan, di ruang sidang, dengan logika, bukan dengan simbol agama. Karena kalau simbol bisa menggantikan hukum, maka korupsi tinggal tunggu giliran disucikan.
Karena kalau semua pejabat cukup bilang "bayar utang" saat ditanya soal aliran dana haram, apa bedanya hukum dengan akal-akalan? Dan kalau itu dibiarkan, cepat atau lambat, yang akan jadi utang sebenarnya adalah kepercayaan rakyat pada keadilan.
Dan ketika kepercayaan itu hilang, jangan salahkan publik jika suatu hari nanti mereka tak lagi percaya pada negara. Karena kalau negara membiarkan narasi menggantikan hukum, maka negara itu sedang membunuh dirinya sendiri dengan cara paling halus, menipu rakyatnya perlahan-lahan.
Lihat postingan ini di Instagram
KALBARONLINE.com – Di sebuah negeri antah berantah yang katanya negara hukum, keadilan bukan lagi soal aturan. Tapi soal siapa yang paling piawai merangkai narasi. Dan sekarang, kita baru saja menyaksikan lahirnya satu jurus pamungkas yang mungkin akan disalin oleh banyak pejabat publik ke depan, jurus "bayar utang".
Pola baru ini sederhana tapi mematikan logika. Seorang penyelenggara negara menerima aliran dana miliaran rupiah dari kontraktor proyek pemerintah. Uangnya dipakai untuk berbagai kebutuhan pribadi. Bangun ruko, beli karpet masjid, hingga aktivitas keluarga. Ketika aparat penegak hukum mulai menyorot, jawabannya simpel, "itu bukan gratifikasi, itu orang bayar utang saya."
Tidak ada bukti perjanjian utang, tidak pernah dicatat dalam LHKPN, tidak ada cicilan atau bunga yang lazim dalam transaksi pinjam-meminjam. Tapi cukup dengan satu kalimat sakti itu, semua seolah beres. Dana yang mencurigakan berubah status, bukan gratifikasi, bukan suap, melainkan pelunasan. Suci kembali.
Dan parahnya, jurus ini justru dilontarkan oleh pejabat yang selama ini dikenal religius, santun, dan penuh ayat di podium. Ironisnya, bahkan saat aparat menyita aset yang diduga hasil aliran dana itu, tak ada sedikit pun rasa gentar. Jawabannya lagi-lagi, "itu dibayar orang karena dia berutang pada saya."
Bayangkan jika dalih ini dibakukan. Bayangkan betapa berbahayanya preseden ini bagi hukum dan logika negara. Karena kalau dibiarkan, ini akan jadi template.
“Anda dapat transfer mencurigakan? Bilang saja itu pembayaran utang lama.”
“Anda dapat mobil, rumah, ruko? Itu bukan gratifikasi, itu tukar guling dari transaksi lisan.”
“Anda pejabat dan penerima dana proyek? Tenang, asal narasi utang rapi, semua bisa disulap.”
Tak hanya itu. Logika "bayar utang" juga membuka jalan baru bagi praktik pencucian uang model lokal. Tak perlu akun bank lepas pantai, tak perlu skema rumit ala Panama Papers. Cukup punya kedekatan dengan penguasa proyek, lakukan transaksi lisan, dan ketika ditanya, tinggal jawab, "sudah dibayar."
Pejabat publik bisa menyimpan aset, membangun properti, menikmati fasilitas, dan tetap tampak bersih secara administratif. Karena satu-satunya dokumen yang dibutuhkan adalah narasi.
Ini jelas melawan semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diatur di negeri antah berantah itu. Karena dalam UU itu, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat negara yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan dalam konteks gratifikasi, beban pembuktian dibalikkan kepada si penerima. Tapi jurus "utang pribadi" tampaknya lebih kuat daripada pasal hukum.
Belum lagi jika dilihat dari aspek moral. Bagaimana mungkin seorang pejabat, yang dipercaya mengelola uang rakyat, bisa bertransaksi miliaran rupiah secara personal dengan kontraktor negara? Kalau memang itu utang pribadi, mengapa tidak pernah dilaporkan sejak awal? Kenapa baru muncul ketika aparat mulai menyelidiki?
Sistem ini sedang dibentuk. Sebuah sistem pembenaran kolektif, di mana siapa pun bisa menyelamatkan diri asal pandai menyusun cerita. Bahkan institusi penegak hukum pun seakan gamang, karena tidak ingin dicap mempolitisasi. Maka muncul-lah kompromi, asal tak terbukti hitam-putih, biarkan abu-abu tetap abu-abu.
Dan publik? Dipaksa percaya. Dipaksa menelan narasi "utang pribadi" seperti kita menelan kenaikan pajak atau harga sembako, dengan diam dan rasa muak.
Coba bayangkan jika logika ini diterapkan di semua sektor. Misalnya, seorang pejabat dinas perizinan menerima hadiah rumah dari pengusaha tambang. Saat ditanya, dia bilang, "Itu pembayaran utang lama waktu saya bantu dia waktu kuliah." Atau bayangkan kepala dinas pendidikan menerima kendaraan mewah dari rekanan penyedia proyek, dan jawabannya adalah, "Dia memang punya utang ke saya waktu saya bantu biaya sekolah anaknya."
Bayangkan pula jika anggota dewan menerima aliran dana dari konsorsium proyek jalan, dan cukup menjawab, "Itu bentuk terima kasih karena dulu saya pernah bantu orangtuanya." Lalu selesai. Tak perlu bukti. Tak perlu pelaporan.
Narasi utang akan jadi benteng baru. Tidak kelihatan di awal, tapi siap muncul saat penyidikan datang. Ia bisa menjadi alasan, sekaligus pelindung. Karena hukum di negeri yang konon katanya menjunjung tinggi keadilan tapi hobi main narasi ini terlalu sering kalah oleh cerita.
Ini berbahaya bukan hanya bagi hukum, tapi bagi generasi berikutnya. Karena yang ditanam adalah contoh buruk, bahwa akal-akalan lebih berguna daripada kejujuran. Bahwa yang penting bukan amanah, tapi pintar bersilat lidah. Bahwa jabatan bukan tanggung jawab, tapi panggung untuk memainkan cerita.
Sementara itu, masyarakat biasa? Hutang Rp5 juta ke bank macet satu minggu saja bisa didatangi debt collector. Tapi ketika pejabat bicara soal utang Rp5 miliar, semua orang harus percaya, dan kalau tidak percaya, dianggap memfitnah.
Di sinilah kita perlu mengembalikan akal sehat publik. Bahwa pinjaman, jika benar, harus tercatat. Harus dilaporkan. Harus diikat perjanjian. Bukan hanya ada ketika dibutuhkan untuk menyelamatkan muka.
Dan aparat penegak hukum pun seharusnya tidak tunduk pada narasi. Seharusnya mampu menembus cerita, menuntut bukti. Karena kalau hanya bergantung pada pengakuan sepihak, maka semua pelaku kejahatan tinggal menghafal satu kalimat ajaib, "Itu karena dia punya utang."
Ini bukan hanya soal satu oknum atau satu kejadian. Ini soal bagaimana kita, sebagai bangsa, mau memelihara sistem keadilan. Apakah kita ingin hukum ditegakkan berdasar logika dan aturan, atau dibengkokkan berdasar cerita?
Publik sebenarnya tak butuh aparat yang galak di depan mikrofon. Publik butuh kepastian bahwa hukum tak bisa dikibuli dengan permainan kata.
Jika negara yang konon katanya masih punya keberanian, yang bahkan kepala negaranya akan mengejar pelaku korupsi sampai ke Antartika, maka setiap narasi "utang pribadi" yang dilempar ke publik harus diuji secara terbuka—di pengadilan, di ruang sidang, dengan logika, bukan dengan simbol agama. Karena kalau simbol bisa menggantikan hukum, maka korupsi tinggal tunggu giliran disucikan.
Karena kalau semua pejabat cukup bilang "bayar utang" saat ditanya soal aliran dana haram, apa bedanya hukum dengan akal-akalan? Dan kalau itu dibiarkan, cepat atau lambat, yang akan jadi utang sebenarnya adalah kepercayaan rakyat pada keadilan.
Dan ketika kepercayaan itu hilang, jangan salahkan publik jika suatu hari nanti mereka tak lagi percaya pada negara. Karena kalau negara membiarkan narasi menggantikan hukum, maka negara itu sedang membunuh dirinya sendiri dengan cara paling halus, menipu rakyatnya perlahan-lahan.
Lihat postingan ini di Instagram
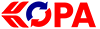
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini