Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 11 Februari 2026 |

Oleh: Syarif Usmulyadi
KEPOLISIAN Republik Indonesia kembali berputar di tempat. Dua puluh lima tahun setelah Reformasi 1998 memisahkan Polri dari TNI, publik masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang tak kunjung terjawab: apakah Polri telah sungguh-sungguh berubah menjadi institusi penegak hukum dalam negara demokrasi, atau justru bertransformasi menjadi pusat kekuasaan baru yang nyaris tak tersentuh pengawasan?
Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini bukan sekadar perdebatan teknis kelembagaan. Ia adalah cermin dari kegagalan negara menata penggunaan kekuasaan koersif secara demokratis. Dalam teori rule of law, aparat penegak hukum seharusnya menjadi penjaga batas kekuasaan, bukan bagian dari masalah kekuasaan itu sendiri. Namun dalam praktik, Polri—terutama melalui fungsi reserse kriminal—seringkali justru berada di jantung persoalan.
Reskrim: Jantung Kekuasaan yang Minim Cahaya
Masalah terbesar Polri hari ini tidak terletak pada seragam, struktur komando, atau retorika profesionalisme. Ia terletak pada praktik penegakan hukum pidana, khususnya di tubuh reserse kriminal (reskrim). Di sanalah hukum bertemu kekuasaan dalam bentuk paling telanjang.
Reskrim memegang kunci proses peradilan pidana: menentukan apakah sebuah peristiwa menjadi perkara hukum atau sekadar arsip mati. Dalam teori democratic policing, diskresi kepolisian memang niscaya. Namun diskresi itu harus bekerja dalam pagar akuntabilitas. Ketika pagar itu rapuh, diskresi berubah menjadi arbitrer, dan hukum menjadi alat seleksi politik, ekonomi, bahkan personal.
Fenomena kriminalisasi selektif, tebang pilih perkara, pemerasan terselubung, hingga penggunaan pasal karet menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya tunduk pada prinsip equality before the law. Dalam bahasa rule of law, hukum masih terlalu sering bekerja sebagai rule by law—aturan yang melayani kekuasaan, bukan membatasinya.
Di titik ini, reskrim tidak lagi sekadar aparat teknis, melainkan simpul kekuasaan. Siapa yang menguasai proses penyidikan, pada hakikatnya menguasai nasib politik, ekonomi, dan kebebasan warga negara.
Reformasi Kepolisian dan Kegagalan Security Sector Reform
Dalam literatur security sector reform (SSR), reformasi aparat keamanan tidak cukup dilakukan melalui restrukturisasi organisasi. Reformasi harus menyentuh tiga lapis sekaligus: kerangka hukum, tata kelola kelembagaan, dan budaya kekuasaan. Indonesia tampak terjebak pada reformasi kosmetik—mengubah struktur tanpa membongkar kultur.
Polri memang telah berpisah dari TNI, namun watak koersif negara tidak serta-merta berkurang. Yang berubah hanyalah aktornya. Alih-alih menjadi civilian police, Polri kerap tampil sebagai institusi semi-militer dengan kewenangan luas dan kontrol terbatas. Inilah
yang oleh banyak analis disebut sebagai unfinished security sector reform. Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini memperlihatkan bahwa negara belum memiliki keberanian politik untuk menundukkan aparat keamanan sepenuhnya pada kontrol sipil
demokratis. Padahal, dalam negara demokrasi, monopoli kekerasan oleh negara hanya sah jika diawasi secara ketat dan transparan.
Posisi Institusional Polri: Di Bawah Presiden, di Atas Hukum?
Salah satu akar masalah reformasi Polri adalah posisi institusionalnya yang langsung berada di bawah Presiden. Secara teoritis, model ini dimaksudkan untuk menjamin netralitas dan efektivitas. Namun dalam praktik, ia justru menciptakan relasi protektif yang berbahaya.
Ketika Polri bermasalah, Presiden berada dalam posisi ambigu: sebagai atasan politik sekaligus simbol penegakan hukum. Akibatnya, koreksi terhadap Polri sering kali setengah hati. Polri pun cenderung menikmati apa yang dalam teori politik disebut sebagai executive shielding—perlindungan politik dari pusat kekuasaan eksekutif.
Alternatif posisi institusional Polri sesungguhnya terbuka. Pertama, menempatkan Polri di bawah institusi Kementerian sebagai institusi sipil administratif, sebagaimana praktik di banyak negara demokrasi. Model ini menegaskan civilian supremacy dan mengurangi konsentrasi kekuasaan. Kedua, menjadikan Polri sebagai lembaga independen konstitusional dengan mekanisme akuntabilitas parlementer yang kuat. Ketiga, model hibrida dengan pemisahan fungsi keamanan publik dan penegakan hukum serius.
Namun perubahan posisi institusional tidak akan bermakna jika jantung penegakan hukum—reskrim—tetap dibiarkan bekerja dalam ruang gelap.
Kompolnas: Pengawas Eksternal yang Dipinggirkan
Dalam desain awal reformasi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dimaksudkan sebagai pengawas eksternal Polri yang mewakili kepentingan publik. Dalam teori democratic oversight, lembaga semacam ini adalah prasyarat agar kepolisian tidak berubah menjadi state within a state.
Masalahnya, Kompolnas hingga kini lebih berfungsi sebagai ornamen demokrasi ketimbang alat kontrol yang efektif. Kewenangannya terbatas, rekomendasinya tidak mengikat, dan aksesnya terhadap jantung kekuasaan Polri—termasuk penegakan hukum oleh reskrim—sangat minim.
Upaya memperkuat Kompolnas kerap menghadapi resistensi ganda. Dari internal Polri, pengawasan eksternal dipandang sebagai ancaman terhadap otonomi institusi. Dari arena politik, terutama DPR RI, penguatan Kompolnas disinyalir kerap dihadang. Di sinilah reformasi Polri bertemu dengan realitas politik transaksional.
Dalam perspektif political economy of reform, pengawasan atas Polri sering kali berbenturan dengan kepentingan elite politik yang juga diuntungkan oleh fleksibilitas penegakan hukum. Polisi yang bisa “diatur” adalah aset politik; polisi yang diawasi secara ketat justru dianggap beban.
Masa Bhakti Kapolri: Membatasi Kekuasaan, Bukan Sekadar Jabatan
Wacana pembatasan masa bhakti Kapolri menjadi dua atau tiga tahun patut dibaca sebagai bagian dari upaya membatasi konsolidasi kekuasaan. Dalam teori organisasi publik, masa jabatan yang terlalu panjang berisiko melahirkan patronase, oligarki internal, dan personalisasi kebijakan.
Pembatasan masa jabatan Kapolri dengan periode tetap dan evaluasi terbuka dapat menjadi instrumen penting reformasi. Ia mencegah kekuasaan terakumulasi pada satu figur dan memaksa pimpinan Polri fokus pada agenda institusional, bukan manuver politik.
Namun pembatasan masa jabatan bukan obat mujarab. Tanpa reformasi sistem promosi, mutasi, dan pengawasan etik—terutama di fungsi reskrim—pergantian Kapolri hanya akan menjadi rotasi elit dalam struktur yang sama.
Reformasi atau Ilusi Demokrasi?
Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh di hadapan aparat penegak hukum. Reformasi kepolisian bukan soal citra, bukan pula soal slogan profesionalisme. Ia adalah pertarungan politik tentang siapa yang mengontrol hukum dan untuk kepentingan siapa hukum ditegakkan.
Selama penegakan hukum pidana masih menjadi ruang gelap kekuasaan, selama pengawasan eksternal seperti Kompolnas dilemahkan, dan selama posisi institusional Polri dibiarkan ambigu, reformasi Polri akan terus menjadi ilusi demokrasi.
Demokrasi tidak selalu runtuh oleh tank dan senjata. Ia bisa mati perlahan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengontrol kekuasaan. Di titik inilah reformasi Polri bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan syarat minimum agar negara hukum tidak berubah menjadi negara kekuasaan. (**)
**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan Dosen Senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.
Oleh: Syarif Usmulyadi
KEPOLISIAN Republik Indonesia kembali berputar di tempat. Dua puluh lima tahun setelah Reformasi 1998 memisahkan Polri dari TNI, publik masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang tak kunjung terjawab: apakah Polri telah sungguh-sungguh berubah menjadi institusi penegak hukum dalam negara demokrasi, atau justru bertransformasi menjadi pusat kekuasaan baru yang nyaris tak tersentuh pengawasan?
Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini bukan sekadar perdebatan teknis kelembagaan. Ia adalah cermin dari kegagalan negara menata penggunaan kekuasaan koersif secara demokratis. Dalam teori rule of law, aparat penegak hukum seharusnya menjadi penjaga batas kekuasaan, bukan bagian dari masalah kekuasaan itu sendiri. Namun dalam praktik, Polri—terutama melalui fungsi reserse kriminal—seringkali justru berada di jantung persoalan.
Reskrim: Jantung Kekuasaan yang Minim Cahaya
Masalah terbesar Polri hari ini tidak terletak pada seragam, struktur komando, atau retorika profesionalisme. Ia terletak pada praktik penegakan hukum pidana, khususnya di tubuh reserse kriminal (reskrim). Di sanalah hukum bertemu kekuasaan dalam bentuk paling telanjang.
Reskrim memegang kunci proses peradilan pidana: menentukan apakah sebuah peristiwa menjadi perkara hukum atau sekadar arsip mati. Dalam teori democratic policing, diskresi kepolisian memang niscaya. Namun diskresi itu harus bekerja dalam pagar akuntabilitas. Ketika pagar itu rapuh, diskresi berubah menjadi arbitrer, dan hukum menjadi alat seleksi politik, ekonomi, bahkan personal.
Fenomena kriminalisasi selektif, tebang pilih perkara, pemerasan terselubung, hingga penggunaan pasal karet menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya tunduk pada prinsip equality before the law. Dalam bahasa rule of law, hukum masih terlalu sering bekerja sebagai rule by law—aturan yang melayani kekuasaan, bukan membatasinya.
Di titik ini, reskrim tidak lagi sekadar aparat teknis, melainkan simpul kekuasaan. Siapa yang menguasai proses penyidikan, pada hakikatnya menguasai nasib politik, ekonomi, dan kebebasan warga negara.
Reformasi Kepolisian dan Kegagalan Security Sector Reform
Dalam literatur security sector reform (SSR), reformasi aparat keamanan tidak cukup dilakukan melalui restrukturisasi organisasi. Reformasi harus menyentuh tiga lapis sekaligus: kerangka hukum, tata kelola kelembagaan, dan budaya kekuasaan. Indonesia tampak terjebak pada reformasi kosmetik—mengubah struktur tanpa membongkar kultur.
Polri memang telah berpisah dari TNI, namun watak koersif negara tidak serta-merta berkurang. Yang berubah hanyalah aktornya. Alih-alih menjadi civilian police, Polri kerap tampil sebagai institusi semi-militer dengan kewenangan luas dan kontrol terbatas. Inilah
yang oleh banyak analis disebut sebagai unfinished security sector reform. Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini memperlihatkan bahwa negara belum memiliki keberanian politik untuk menundukkan aparat keamanan sepenuhnya pada kontrol sipil
demokratis. Padahal, dalam negara demokrasi, monopoli kekerasan oleh negara hanya sah jika diawasi secara ketat dan transparan.
Posisi Institusional Polri: Di Bawah Presiden, di Atas Hukum?
Salah satu akar masalah reformasi Polri adalah posisi institusionalnya yang langsung berada di bawah Presiden. Secara teoritis, model ini dimaksudkan untuk menjamin netralitas dan efektivitas. Namun dalam praktik, ia justru menciptakan relasi protektif yang berbahaya.
Ketika Polri bermasalah, Presiden berada dalam posisi ambigu: sebagai atasan politik sekaligus simbol penegakan hukum. Akibatnya, koreksi terhadap Polri sering kali setengah hati. Polri pun cenderung menikmati apa yang dalam teori politik disebut sebagai executive shielding—perlindungan politik dari pusat kekuasaan eksekutif.
Alternatif posisi institusional Polri sesungguhnya terbuka. Pertama, menempatkan Polri di bawah institusi Kementerian sebagai institusi sipil administratif, sebagaimana praktik di banyak negara demokrasi. Model ini menegaskan civilian supremacy dan mengurangi konsentrasi kekuasaan. Kedua, menjadikan Polri sebagai lembaga independen konstitusional dengan mekanisme akuntabilitas parlementer yang kuat. Ketiga, model hibrida dengan pemisahan fungsi keamanan publik dan penegakan hukum serius.
Namun perubahan posisi institusional tidak akan bermakna jika jantung penegakan hukum—reskrim—tetap dibiarkan bekerja dalam ruang gelap.
Kompolnas: Pengawas Eksternal yang Dipinggirkan
Dalam desain awal reformasi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dimaksudkan sebagai pengawas eksternal Polri yang mewakili kepentingan publik. Dalam teori democratic oversight, lembaga semacam ini adalah prasyarat agar kepolisian tidak berubah menjadi state within a state.
Masalahnya, Kompolnas hingga kini lebih berfungsi sebagai ornamen demokrasi ketimbang alat kontrol yang efektif. Kewenangannya terbatas, rekomendasinya tidak mengikat, dan aksesnya terhadap jantung kekuasaan Polri—termasuk penegakan hukum oleh reskrim—sangat minim.
Upaya memperkuat Kompolnas kerap menghadapi resistensi ganda. Dari internal Polri, pengawasan eksternal dipandang sebagai ancaman terhadap otonomi institusi. Dari arena politik, terutama DPR RI, penguatan Kompolnas disinyalir kerap dihadang. Di sinilah reformasi Polri bertemu dengan realitas politik transaksional.
Dalam perspektif political economy of reform, pengawasan atas Polri sering kali berbenturan dengan kepentingan elite politik yang juga diuntungkan oleh fleksibilitas penegakan hukum. Polisi yang bisa “diatur” adalah aset politik; polisi yang diawasi secara ketat justru dianggap beban.
Masa Bhakti Kapolri: Membatasi Kekuasaan, Bukan Sekadar Jabatan
Wacana pembatasan masa bhakti Kapolri menjadi dua atau tiga tahun patut dibaca sebagai bagian dari upaya membatasi konsolidasi kekuasaan. Dalam teori organisasi publik, masa jabatan yang terlalu panjang berisiko melahirkan patronase, oligarki internal, dan personalisasi kebijakan.
Pembatasan masa jabatan Kapolri dengan periode tetap dan evaluasi terbuka dapat menjadi instrumen penting reformasi. Ia mencegah kekuasaan terakumulasi pada satu figur dan memaksa pimpinan Polri fokus pada agenda institusional, bukan manuver politik.
Namun pembatasan masa jabatan bukan obat mujarab. Tanpa reformasi sistem promosi, mutasi, dan pengawasan etik—terutama di fungsi reskrim—pergantian Kapolri hanya akan menjadi rotasi elit dalam struktur yang sama.
Reformasi atau Ilusi Demokrasi?
Gonjang-ganjing reformasi Polri hari ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh di hadapan aparat penegak hukum. Reformasi kepolisian bukan soal citra, bukan pula soal slogan profesionalisme. Ia adalah pertarungan politik tentang siapa yang mengontrol hukum dan untuk kepentingan siapa hukum ditegakkan.
Selama penegakan hukum pidana masih menjadi ruang gelap kekuasaan, selama pengawasan eksternal seperti Kompolnas dilemahkan, dan selama posisi institusional Polri dibiarkan ambigu, reformasi Polri akan terus menjadi ilusi demokrasi.
Demokrasi tidak selalu runtuh oleh tank dan senjata. Ia bisa mati perlahan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengontrol kekuasaan. Di titik inilah reformasi Polri bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan syarat minimum agar negara hukum tidak berubah menjadi negara kekuasaan. (**)
**Penulis merupakan pengamat sosial politik dan Dosen Senior Ilmu Politik di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.
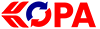
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini